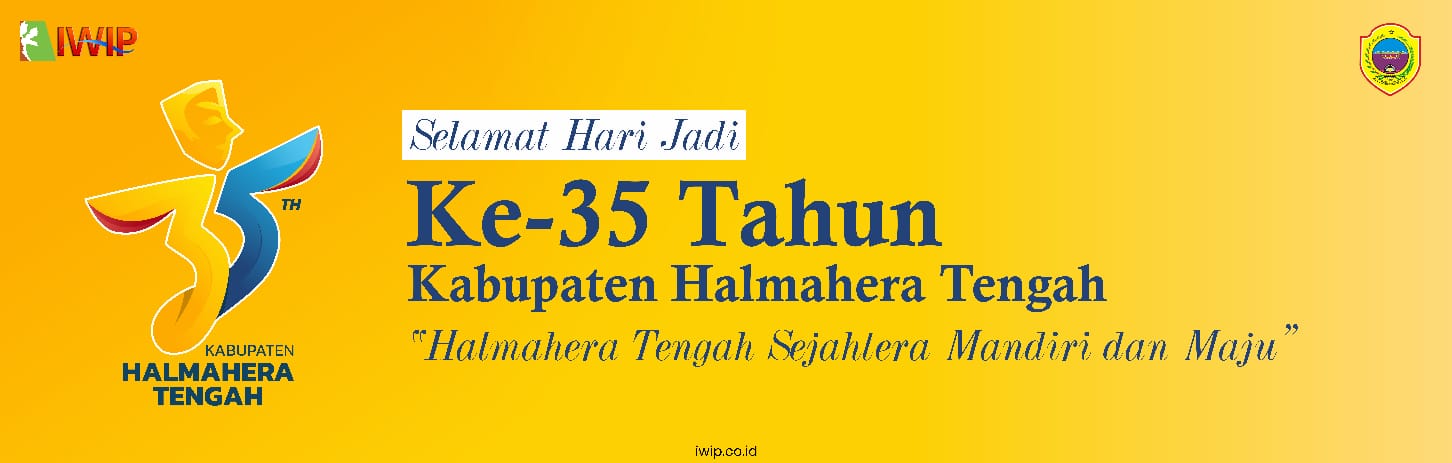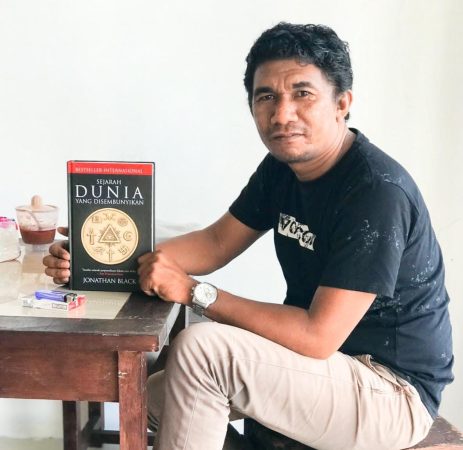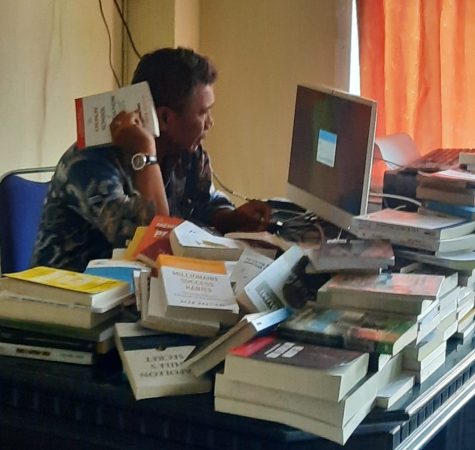“Marimoi Ngone Futuru”
Oleh: Arafik A. Rahman
DIBAWAH, langit yang teduh, di kaki gunung Gamalama yang penuh pusaka, di Foris Lamo Kedaton kesultanan Ternate, pada 29 Juli 2025 menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa bersejarah yang bukan saja menyentuh sisi budaya. Tetapi juga menggugah kembali konektivitas identitas budaya yang sempat tertidur dalam bayang-bayang modernisasi.
Di tempat sakral yang menyimpan aroma masa lalu dan gema kejayaan maritim itu, Sultan Ternate, Hidayatullah Syah dengan khidmat melantik Perangkat Adat Morotai, sebuah langkah penting yang melampaui seremoni biasa. Ini adalah pertautan kembali antara akar dan batang, antara sejarah dan masa depan, antara Morotai dan Ternate dalam satu nafas: Mari Moi Ngone Futuru: bersatu kita kuat. Pelantikan ini tak sekadar seremoni simbolik, melainkan bagian dari upaya merawat dan menyulam kembali kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Dalam dunia yang bergerak cepat oleh arus globalisasi dan gemuruh teknologi, perangkat adat tampil sebagai pedang dan perisai nilai. Sebagai pengingat bahwa sebelum ada republik, sebelum ada negara-bangsa, telah ada kosmologi budaya yang mengatur harmoni antara manusia dan alam, antara pemimpin dan rakyat, antara tanah dan laut, antara manusia dengan Tuhannya. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam merawat adat istiadat Kesultanan Ternate yang sejak berabad silam telah menjadi pusat peradaban di kawasan timur Nusantara.
Morotai, sebagai pulau yang dulunya merupakan bagian dari jantung kesultanan, kini kembali dihidupkan dengan semangat kebudayaan dan marwah adat. Perangkat adat yang dilantik bukan sekadar penjaga upacara, tetapi penjaga jiwa kolektif yang menghubungkan Morotai dengan akar sejarahnya, sebuah sejarah yang kaya, dalam dan penuh hikmah. Dalam pandangan akademik, pelantikan ini juga bermakna sebagai revitalisasi kelembagaan. Struktur organisasi Kesultanan Ternate diperkuat, diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Di tengah tarikan kuat modernisasi dan homogenisasi nilai-nilai global, kesultanan tidak hanya ingin bertahan sebagai simbol sejarah, melainkan sebagai entitas sosial-budaya yang relevan, adaptif dan responsif. Teori Cultural Resilience dari Fikret Berkes dalam bukunya “Sacred Ecology” (Routledge, 2012), menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan eksternal globalisasi, selama sistem pengetahuan lokal dan struktur sosial-budaya mereka tetap hidup dan aktif.

Karenanya, revitalisasi adat bukan bentuk nostalgia, melainkan strategi bertahan dan bangkit dalam pusaran perubahan zaman. Morotai bukanlah tanah asing dalam khazanah Kesultanan Ternate. Dari zaman awal hingga era Perang Pasifik 1944, pulau ini adalah halaman penting dalam kitab sejarah Maluku Utara. Pada masa itu, setelah kekuatan Jepang dikalahkan, Jenderal Douglas Mac Arthur memberikan tiga pilihan kepada Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah, salah satu putra terbaik negeri ini:
1. Bergabung dengan Amerika Serikat sebagai negara bagian,
2. Merdeka sebagai negara sendiri, atau
3. Bergabung dengan Indonesia.
Sejarah mencatat, Sultan Iskandar dengan visi kultural, keislaman dan kenusantaraannya, ia memilih bergabung dengan Bung Karno dan menjadikan wilayah kesultanan sebagai bagian sah dari Republik Indonesia. Pilihan itu bukan keputusan pragmatis, melainkan refleksi mendalam dari tanggung jawab sejarah dan kesadaran geopolitik yang mengakar pada semangat persatuan dan harga diri bangsa.
Tak dapat dimungkiri, sejarah juga mencatat Morotai sebagai pangkalan pertahanan strategis Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Pulau ini, yang secara kultural berada dalam wilayah Kesultanan Ternate, kemudian bertransformasi menjadi Daerah Otonom Baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Namun, transformasi administratif itu tidak serta-merta memutus nadinya sebagai wilayah budaya. Sebab dalam pemahaman leluhur, tanah bukan hanya tempat berpijak, tetapi juga tempat menjaga nilai, harga diri dan kesejahteraan rakyat.
Dengan dilantiknya perangkat adat, kita kembali menegaskan bahwa walaupun struktur birokrasi berubah, kekuatan kultur tetap hidup dan menyala. Ia bukan sekadar romantika masa lalu, tapi merupakan amanah para leluhur: menjaga tanah, laut, dan manusia yang hidup di atasnya, agar tetap sejahtera, berbudaya dan bermartabat.
“Mari Moi Ngone Futuru” bukan hanya slogan. Ia adalah semangat kolektif yang menghidupkan kembali roh kebersamaan dalam perbedaan, mengajak kita menanam ulang nilai-nilai yang mulai tergerus zaman. Dengan bersatu, nilai-nilai adat dan tradisi tidak akan tersingkir dari ruang publik, justru akan menjadi pondasi moral dan sosial dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks.
Pelantikan ini mengajarkan kita bahwa sejarah bukanlah beban, melainkan pelita; bahwa adat bukanlah penghalang kemajuan, melainkan jembatan menuju masa depan yang berakar kuat dan menjulang tinggi.
Di bawah cahaya Kedaton yang mulai temaram sore itu, ketika doa-doa dan syair adat dilantunkan, kita seperti mendengar suara para leluhur yang lama diam: “Jangan biarkan kami hanya hidup di buku sejarah. Hidupkan kami dalam sikapmu, dalam langkahmu, dalam pilihanmu.” Dan hari itu, Morotai menjawab panggilan itu.
“Kadang, yang kita kira masa lalu telah selesai, justru menunggu kita untuk menyentuhnya kembali, agar kita tahu ke mana harus melangkah”. (**)