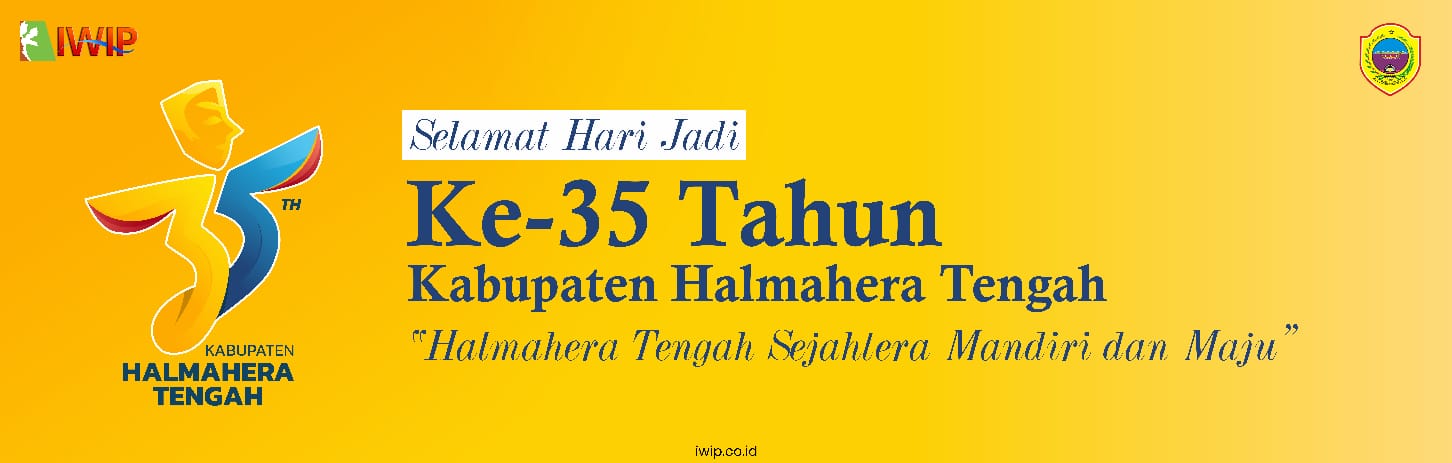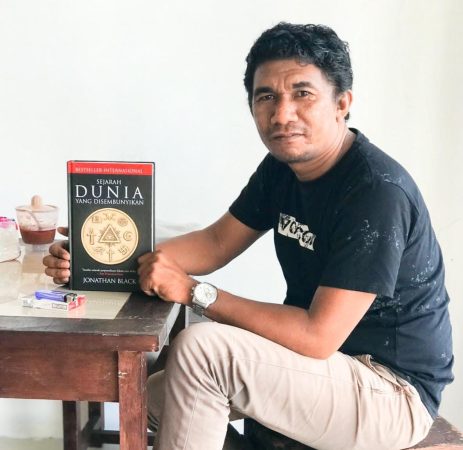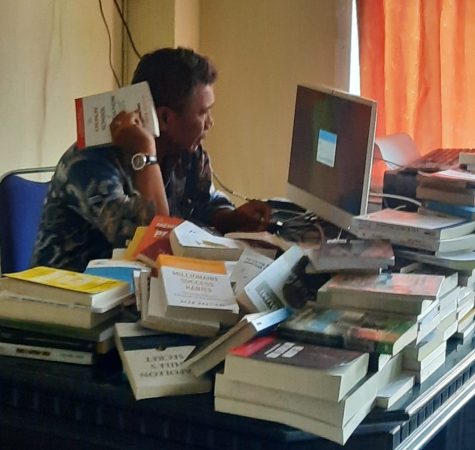“Ketika Harta Membutakan, Ketika Kuasa Melupakan”
(Sebuah Catatan Refleksi Kehidupan)
Oleh ; Arafik A Rahman
“The measure of a man is what he does with power.” Ukuran sejati seorang manusia terlihat dari apa yang ia lakukan ketika memegang kekuasaan.” – Plato
DALAM, perjalanan hidup manusia, jarang ada ujian yang seberat ujian harta dan kuasa. Orang sering terlihat sederhana, ramah dan penuh perhatian sebelum mendapatkan keduanya. Namun, begitu uang menumpuk atau kursi kekuasaan diraih, wajah asli mulai terbuka. Perubahan itu tak jarang membuat orang-orang terdekat merasa asing, bahkan kehilangan sosok yang pernah mereka kagumi.
Realitas sosial kita menyimpan banyak kisah tentang sahabat yang berubah setelah kaya. Ketika masih susah, ia sering singgah, banyak tertawa dan merasa semua orang adalah keluarga. Namun, begitu rekeningnya gemuk, ia tiba-tiba menjaga jarak. Teman lama diabaikan dan hanya lingkaran baru yang dianggap layak. Di sinilah, harta yang awalnya sekadar alat, justru membutakan mata hati manusia.
Fenomena serupa juga berlaku pada para pemimpin. Sebelum dipilih, seorang calon seringkali terlihat sederhana, mudah berkomunikasi, chatting, telpon dan ditelpon, sangat bersahaja dan ramah. Ia datang ke pasar, menyalami nelayan, bahkan duduk bersama rakyat kecil sembari makan pisang goreng. Namun, seiring berjalannya waktu setelah duduk di kursi empuk, semua berubah. Telepon sulit diangkat, chat sulit dibalas, janji terasa hambar dan rakyat kembali menjadi penonton yang tak penting.
Sejarah memberi kita cermin. Lihatlah sosok Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang dikenal sebagai philosopher king. Di tengah gemerlap kekuasaan, ia justru menulis Meditations—sebuah renungan tentang kerendahan hati, kefanaan hidup, dan pentingnya keadilan. Kekayaan dan kuasa yang dimilikinya tidak menjadikan ia sombong, melainkan bijak. Ia menjadi bukti bahwa kuasa bisa selaras dengan kebijaksanaan.
Sebaliknya, sejarah juga mencatat pemimpin absolut yang menjerumuskan bangsanya ke dalam penderitaan. Louis XIV dari Perancis, yang menyebut dirinya sebagai “L’État, c’est moi” (Negara adalah saya), menjadikan kekuasaan sebagai alat pemujaan diri. Kemewahan istana Versailles berdiri di atas penderitaan rakyat. Ia adalah simbol betapa kuasa yang absolut sering berujung pada kelupaan: lupa pada tanggung jawab, lupa pada kesederhanaan, dan lupa pada rakyat. Akhirnya ia tumbang dan kepalanya dipenggal, dalam revolusi Prancis di abad ke 18 ketika itu.
Dari dua cermin sejarah itu, kita belajar bahwa harta dan kuasa bukanlah masalah pada dirinya, melainkan pada manusia yang memegangnya. Mereka yang bijak menjadikannya sebagai amanah, sementara mereka yang lalai membiarkannya menjadi jebakan. Oleh sebab itu, pengaruh harta dan kuasa terhadap watak manusia akan selalu menjadi diskursus penting, baik dalam ranah akademis maupun kehidupan sehari-hari.
Psikolog sosial Dacher Keltner dalam bukunya The Power Paradox (2016) menyatakan bahwa kuasa pada awalnya sering diraih karena seseorang rendah hati, empatik dan komunikatif. Namun, begitu kuasa itu diraih, sifat-sifat mulia tersebut sering terkikis, digantikan oleh arogansi dan jarak sosial. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa pemimpin yang dulu sederhana berubah drastis setelah memegang jabatan.
Begitu pula dengan uang. Ekonom Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century (2014) mengungkap bahwa akumulasi kekayaan tak hanya mengubah struktur sosial, tapi juga mengubah relasi manusia. Orang kaya lebih mudah membangun benteng sosial, membatasi interaksi dengan kelas lain, bahkan menciptakan ilusi bahwa mereka lebih bermartabat dibandingkan yang miskin.
Cerita sehari-hari juga tak kalah nyata. Ada sahabat yang dulunya suka makan nasi kuning di pinggir jalan, tertawa tanpa beban, kini merasa jijik dengan tempat itu. Ketika diajak berkumpul, ia berkilah sibuk dengan “urusan besar”. Padahal, di balik kata-kata itu tersembunyi gengsi yang tak lagi bisa menerima kesederhanaan.
Pada titik ini, kita bisa melihat harta dan kuasa sebagai alat uji. Ujian ini tak selalu berakhir buruk, tetapi peluang untuk tergelincir amat besar. Masyarakat sering berkata, “Jika ingin benar-benar mengenal seseorang, lihatlah ketika ia kaya atau berkuasa.” Pepatah ini lahir dari realitas sosial yang terus berulang sepanjang zaman.
Menariknya, ada pula kisah-kisah lucu yang menyimpan ironi. Seorang teman, misalnya, tiba-tiba mengubah gaya bicara setelah jadi pejabat desa. Ia tak lagi menyebut “mohon dilaksanakan” melainkan “segera jika tidak tunjangan mu dipotong”. Padahal, dulu ia bercanda paling keras di warung kopi. Kini, setiap kalimatnya seperti pidato resmi. Lucu, sekaligus menyedihkan, karena perubahan itu menunjukkan bagaimana kursi jabatan bisa mengubah bahasa dan perilaku.
Pertanyaannya, apakah harta dan kuasa selalu buruk?.Tentu tidak. Harta dapat menjadi sarana membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu sesama. Kuasa dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan mengubah kebijakan demi kebaikan rakyat. Artinya, harta dan kuasa netral, tergantung siapa yang mengelola.
Jadi, penting bagi manusia untuk memiliki fondasi moral yang kuat sebelum menerima keduanya. Tanpa pondasi, harta akan menjadi candu dan kuasa akan menjadi tirani. Namun, dengan pondasi, keduanya bisa menjadi berkah yang mensejahterakan banyak orang. Dalam konteks ini, religiusitas, moral dan etika memainkan peran penting. Hampir semua tradisi keagamaan menekankan bahaya keserakahan dan mengajarkan kesederhanaan.
Misalnya, dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam tradisi Buddha, kekayaan dilihat sebagai ujian keterikatan yang dapat menghalangi jalan pencerahan. Di era modern, integritas dan transparansi juga menjadi jawaban. Sistem yang kuat mampu membatasi potensi penyalahgunaan kuasa dan kediktatoran gaya baru. Namun, sistem tanpa manusia berintegritas hanyalah aturan kosong. Akhirnya, kembali lagi pada individu: apakah ia akan membiarkan dirinya dibutakan dan dilupakan, atau tetap sadar dan rendah hati.
Kita semua mungkin pernah menjadi saksi perubahan sahabat atau pemimpin. Ada rasa kecewa, ada rasa asing, bahkan kadang ada luka. Namun, pengalaman itu sekaligus mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada wajah manis sebelum seseorang berkuasa atau kaya. Oleh karenanya, bijaklah menyikapi setiap perubahan. Jangan terlalu terkejut jika sahabat menjauh setelah kaya, atau jika pemimpin menjadi angkuh setelah berkuasa.
Itu bagian dari realitas manusia. Yang penting adalah bagaimana kita tetap teguh menjaga diri agar tidak terjebak pada jebakan yang sama. Pada akhirnya, setiap orang bisa saja mendapat giliran diuji dengan harta atau kuasa, entah besar atau kecil. Bisa jadi kita diuji dengan posisi yang baru; ketua, kepala desa, kepala dinas, anggota parlemen atau menjadi Bupati dan Gubernur. Di titik itu, watak sejati kita pun akan terungkap.
Maka, jangan alergi dikritik, penting juga untuk bercermin atau berintrospeksi: apakah kita sendiri cukup kuat jika suatu hari dipercaya?. Pertanyaan ini jauh lebih mendalam daripada sekadar mengomentari perubahan orang lain. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan Plato, ukuran manusia sejati terletak pada bagaimana ia memperlakukan harta dan kuasa. Apakah ia akan buta dan lupa, atau tetap sadar dan mengingat bahwa keduanya hanyalah titipan sementara. (**)