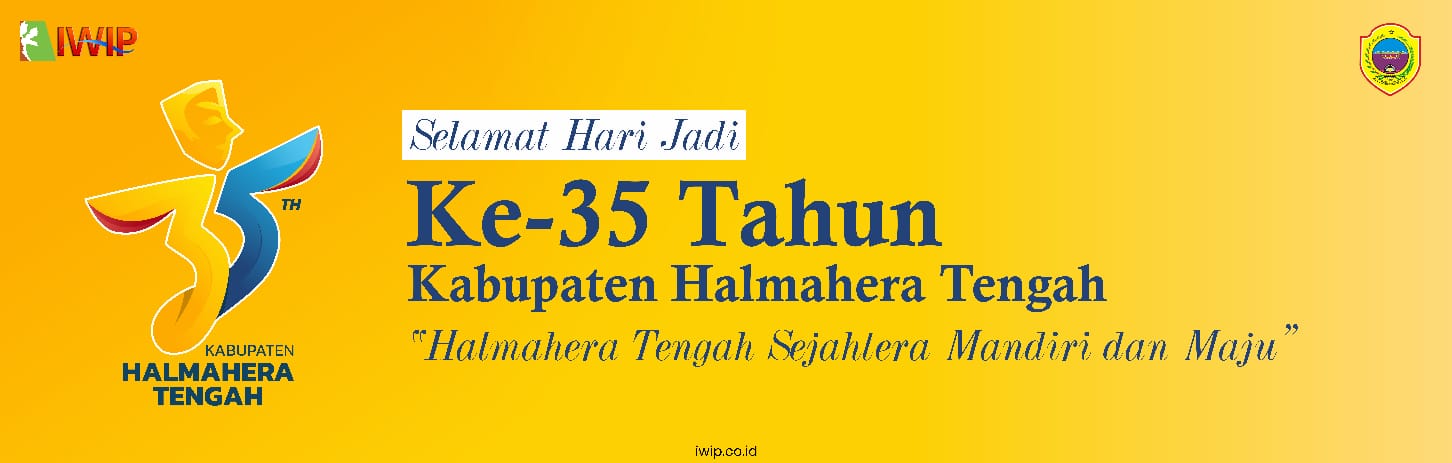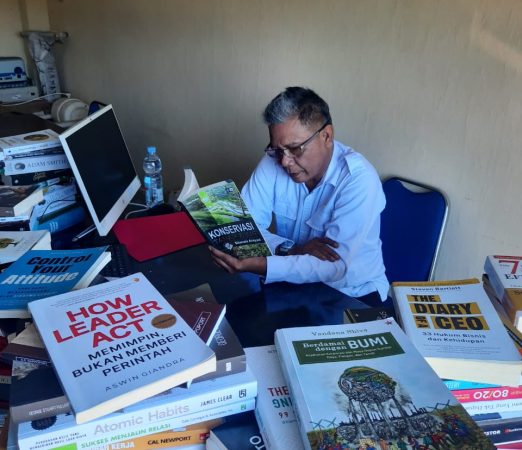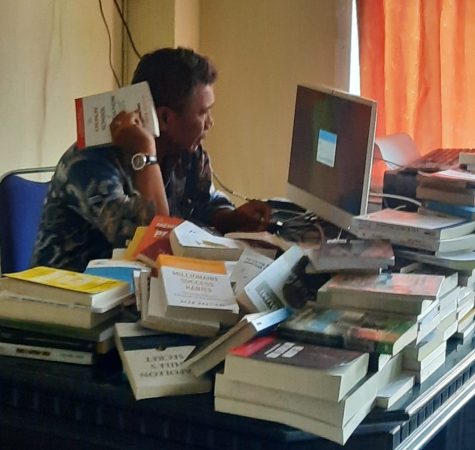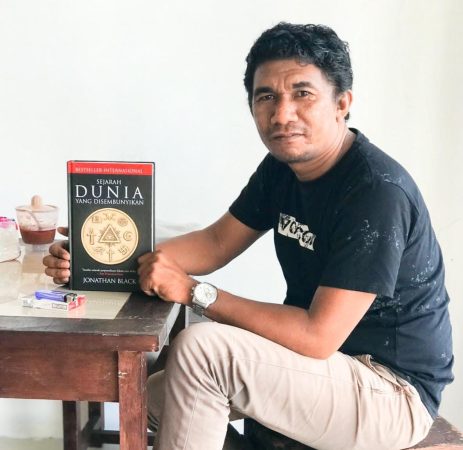
“Pancasila dan Dialektika Sejarah Indonesia: Falsafah yang Selalu Diuji”
Oleh ; Arafik A Rahman
“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” Mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu, akan dihukum untuk mengulanginya kembali.— George Santayana, The Life of Reason (1905)
PANCASILA, itu bukan datang sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil tabrakan ide antara tokoh-tokoh bangsa yang berupaya mencari dasar kehidupan bersama. Sejak sidang BPUPKI tahun 1945, terlihat betapa mendasar pertanyaan itu: apakah Indonesia berdiri di atas satu agama, ataukah di atas falsafah kebangsaan yang lebih inklusif?.
Bung Karno menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag, fondasi filsafat bagi bangsa yang plural. Dengan lima sila yang menampung unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, ia menjadi jalan tengah yang menghindari dominasi ideologi tunggal. Secara filosofis, Pancasila adalah upaya merumuskan consensus eticum: kesepakatan etis yang lahir dari pluralitas masyarakat nusantara.
Di sinilah ia menempati posisi unik: bukan sekadar ideologi politik, tetapi pandangan hidup bersama. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa cita-cita Pancasila selalu berada dalam ujian. Setelah kemerdekaan, bangsa ini harus menghadapi tarik-menarik ideologi: nasionalisme, komunisme dan Islam politik. Semua merasa memiliki legitimasi untuk menentukan arah negara.
Pada dekade 1950-an menjadi panggung bagi pertarungan ideologi itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit dengan kekuatan massa besar, mengusung gagasan marxisme-leninisme sebagai solusi radikal atas ketidakadilan sosial. Di sisi lain, partai-partai Islam menuntut agar dasar negara lebih condong pada syariat, mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Sementara itu, kalangan nasionalis dan militer berusaha menjaga posisi dominannya dalam politik.
Pancasila yang awalnya diposisikan sebagai titik temu, justru ditarik ke kanan dan ke kiri, tergantung siapa yang menafsirkan. Filosofisnya, bangsa ini memasuki dialektika Hegelian: tesis kemerdekaan, antitesis berupa konflik ideologi dan sintesis yang terus dicari namun tak kunjung stabil.
Memasuki awal 1960-an, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom: Nasionalisme, Agama, Komunisme, sebagai usaha mengawinkan kekuatan besar bangsa. Secara filosofis, Nasakom adalah eksperimen politik untuk menjaga keseimbangan, meski dalam praktiknya lebih sering menimbulkan kecurigaan antar pihak.
Ketegangan memuncak pada malam 30 September 1965. Enam jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Indonesia. Secara filsafat politik, G30S adalah simbol hancurnya kepercayaan antar-ideologi. Nasionalis, komunis, Islam dan militer tidak lagi menemukan titik temu.
Pancasila yang seharusnya menjadi rumah bersama, nyaris runtuh oleh intrik kekuasaan dan ideologi yang saling meniadakan. Dari tragedi itu, lahir pula luka besar: pembantaian massal, penghilangan nyawa, dan trauma kolektif yang hingga kini masih menyisakan perdebatan. Di sinilah tampak sisi rapuh bangsa ketika Pancasila gagal dijaga dengan kearifan.
Tahun 1966, Orde Baru berdiri dengan menafsirkan Pancasila secara tunggal. Ia dijadikan ideologi final yang tidak boleh digugat. Pancasila masuk ke ruang kelas, disertai penataran dan doktrinasi. Namun dalam proses itu, makna filosofisnya justru sering terkubur. Dari perspektif filsafat, penyeragaman tafsir justru menutup ruang dialog kritis. Padahal, esensi Pancasila adalah keterbukaan, musyawarah dan sintesis dari pluralitas. Tragedi 1965–1966 memperlihatkan paradoks: ketika Pancasila tidak dipahami sebagai kesadaran bersama, ia bisa dijadikan alat legitimasi untuk menyingkirkan pihak lain.
Kata Immanuel Kant dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), “manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat.” Begitu pula dengan Pancasila: ia bukan alat penguasa, melainkan tujuan luhur yang menjaga martabat bangsa. Hari ini, ketika kita memperingati peristiwa kelam 1965 dan merayakan Hari Kesaktian Pancasila, kita diingatkan untuk tidak mengulangi luka sejarah. Bangsa ini harus terus belajar menafsirkan Pancasila secara terbuka dan kritis.
Nilai ketuhanan harus mengajarkan toleransi, bukan kebencian. Nilai kemanusiaan harus mendorong penghormatan terhadap hak hidup, bukan justru melahirkan pembunuhan massal. Nilai persatuan harus merajut, bukan memecah. Nilai kerakyatan harus menumbuhkan musyawarah, bukan sekadar legitimasi formal. Dan nilai keadilan sosial harus nyata dirasakan, bukan sekadar retorika politik.
Dengan cara itu, Pancasila kembali pada hakikatnya: bukan dogma mati, melainkan falsafah hidup yang menuntun bangsa. Ia adalah living philosophy, filsafat yang terus bergerak, diuji oleh zaman, dan dibentuk ulang oleh generasi yang lahir kemudian. Sejarah 1965–1966 memberi kita luka, tetapi juga pelajaran. Bahwa bangsa ini hanya bisa bertahan jika menjadikan Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan kesadaran moral bersama.
Hari ini, kita tidak hanya mengenang tragedi, tetapi juga meneguhkan kembali janji kebangsaan. Dengan harapan dan doa untuk bangsa ini, marilah kita ucapkan:
“Selamat Hari Kesaktian Pancasila, jayalah Pancasila ku, jayalah Indonesia ku.” (**)