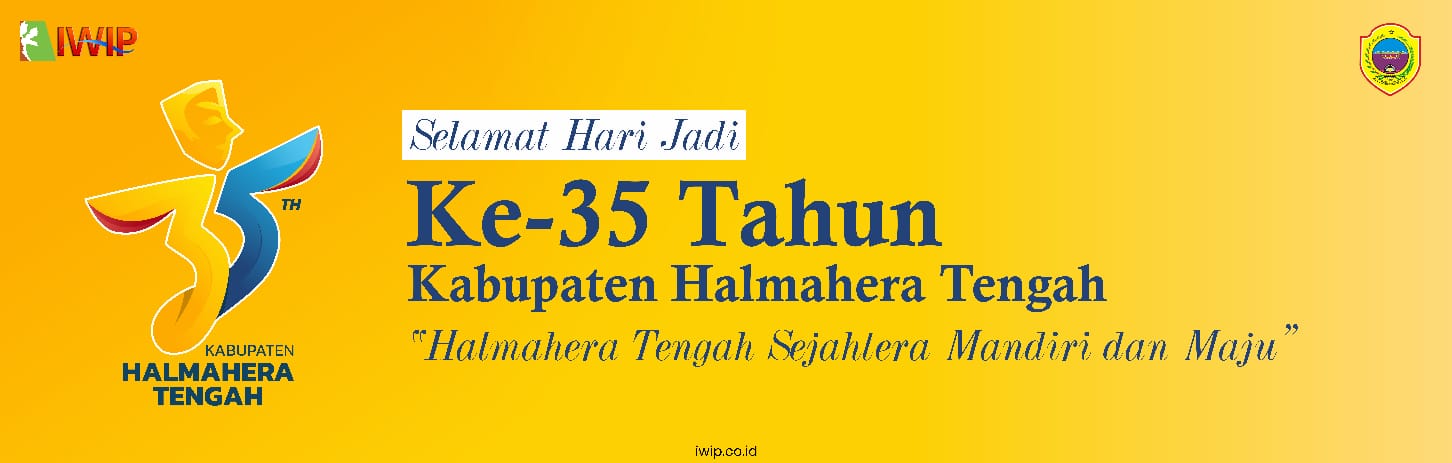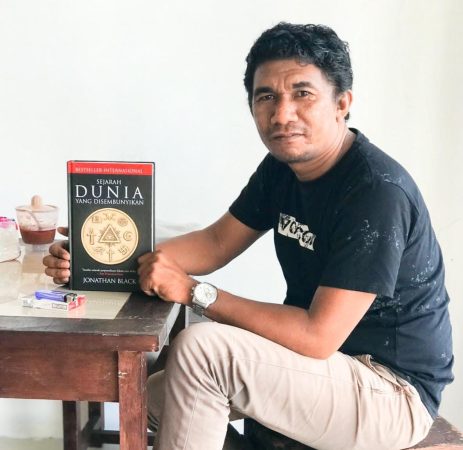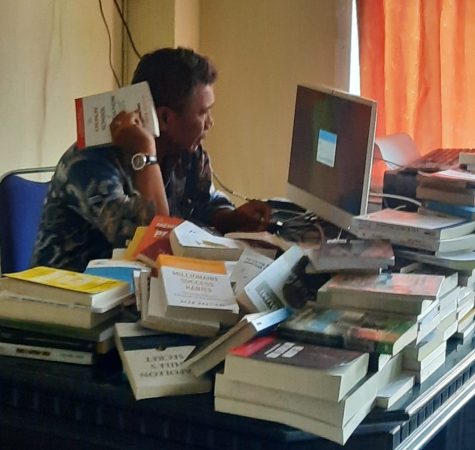Gerak yang Menyimpan Sejarah: Tafsir Sosial atas Cakalele dan Tide-tide”
Oleh ; Arafik A Rahman
“Tarian tradisional bukanlah sekadar hiburan, melainkan bentuk teks budaya yang hidup. Ia merekam trauma, merayakan harapan dan menyusun kembali identitas dalam gerak yang diwariskan,” (James T. Siegel, Cultural Anthropologist, Cornell University).
Di jantung kepulauan rempah, di bawah bayang empat kerajaan tua: Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, atau yang dikenal sebagai Moloku Kie Raha. Hidup dua tarian yang tak sekadar menghentak dan mengalun tapi juga menyimpan petuah sejarah, makna sosial dan filosofi budaya. Mereka adalah Cakalele dan Tide-tide, dua wajah budaya yang saling melengkapi: Satu mengandung amarah yang sakral, satunya mengalir dalam senyum dan tatapan yang menggoda.
Cakalele: Ketika Tubuh Menjadi Senjata dan Sambutan. Ia adalah tarian perang tradisional yang berasal dari warisan leluhur di Moloku Kie Raha. Dengan parang dan salawaku di tangan, para penarinya bukan sekadar menari, melainkan menghidupkan kembali ingatan tentang perlawanan, martabat dan persekutuan suci. Gerakan meloncat, menghentak, dan menyilang parang tak dilakukan sembarangan, ada ritus tubuh yang dipelajari turun-temurun dari kampung ke kampung.
Menariknya, Cakalele tidak seragam. Di Maluku Utara, setiap kabupaten dan kota memiliki varian lokalnya masing-masing. Di Ternate, Cakalele menampilkan peran Kapita Laut yang kharismatik; di Tidore, ia lebih ritmis dan penuh dengan nuansa kerajaan; di Halmahera, suara tifa yang memekik seperti nyawa tarian itu sendiri.
Ada Cakalele untuk perang, namun ada pula Cakalele untuk jamuan tamu, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh penting, tamu adat, atau dalam upacara penyambutan pemimpin. Ia bisa menggetarkan, bisa juga mengayomi, seperti dua sisi dari satu pedang yang diwariskan nenek moyang.
Dalam pandangan Siegel (2005), Cakalele adalah “the memory in motion” ingatan kolektif yang diwujudkan dalam gerak. Tubuh yang menari bukan tubuh individual, tetapi tubuh komunitas yang sedang menyuarakan sejarah dan identitas.
Tide-tide: Tatapan, Senyuman dan Diplomasi Tubuh. Jika Cakalele bicara dalam teriakan dan hentakan kaki, maka Tide-tide berbicara dalam isyarat, pantun dan senyum. Ia adalah tarian pergaulan tetapi bukan sekadar hiburan. Dalam ayunan tangan perempuan, terselip dua kemungkinan makna: memanggil atau menolak. Dalam tatapan mata dan senyuman, tersimpan keputusan: menerima atau berpaling.
Dalam Tide-tide, tubuh bukan hanya gerak, ia adalah kode, diplomasi dan bahkan penolakan yang halus. Tarian ini, menjadi ruang simbolik dimana pemuda-pemudi Maluku Utara berinteraksi, bercanda, bahkan saling menguji perasaan. Ia lahir dari akar tradisi masyarakat yang egaliter, namun penuh sopan santun. Antropolog budaya Martha Manoe (2012) menyebut, “Tide-tide adalah arena di mana komunikasi sosial dilatih dalam bentuk estetika.” Dan dalam dunia yang makin kehilangan cara menyampaikan perasaan secara santun, Tide-tide tetap mengajarkan bahwa cinta bisa dinyanyikan, bukan diteriakkan.
Cakalele dan Tide-tide tidak dapat dilepaskan dari kerangka budaya Moloku Kie Raha. Mereka bukan tarian generik, melainkan manifestasi lokal dari kekuasaan, nilai dan struktur masyarakat adat. Cakalele adalah cermin dari relasi vertikal: antara rakyat, pemimpin dan leluhur. Sementara Tide-tide adalah wajah dari relasi horizontal: antar warga, antar hati dan antar lagu.
Keduanya merawat identitas dan perasaan kolektif. Dalam masyarakat yang kerap dihadapkan pada trauma penjajahan, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan pembangunan, tarian-tarian ini hadir sebagai pengikat bukan sekadar simbol masa lalu, tapi tanda yang hidup di masa kini.
Kita harus berhati-hati agar keduanya tidak mati di atas panggung-panggung kaku atau festival pariwisata yang hampa makna. Kita harus merawat bukan hanya geraknya, tetapi roh yang tersembunyi dalam hentakan kaki dan kedipan mata itu. Budaya bukan benda yang disimpan, tetapi api yang terus dinyalakan dengan penghormatan, pemahaman, dan pelibatan generasi muda.
“Tak semua sejarah ditulis dengan pena. Beberapa ditarikan dengan parang dan senyum.”
Referensi :
– Siegel, James T. (2005). Naming the Witch. Stanford University Press.
– Manoe, Martha. (2012). Tide-tide: Seni Tubuh dan Negosiasi Sosial dalam Tradisi Maluku. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Indonesia.
Catatan akhir:
Esai ini dapat disempurnakan lagi dengan menambahkan referensi lapangan dan wawancara tokoh adat dari masing-masing wilayah. (**)