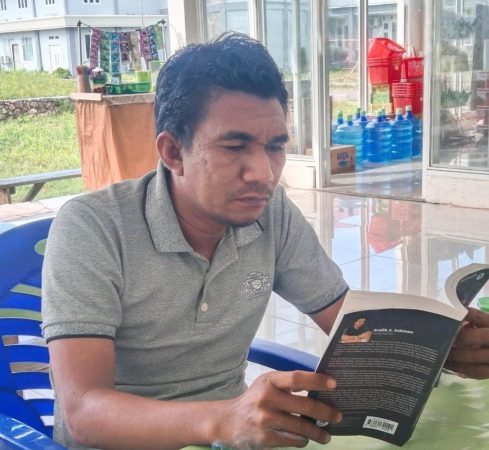“Menimbang Ulang Keserentakan Pemilu,Tanggapan Atas Putusan MK NO. 135/PUU-XXII/2024,”
Oleh ; Zulfikar Kusuma Akbar, S.H (Pengacara Pada Volksgeist Advocates Law Firm Jakarta)
PUTUSAN, Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan respons yudisial atas permohonan pengujian konstitusionalitas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Perludem dengan dasar argumentasi bahwa model pemilu serentak lima kotak yang digelar bersamaan antara pemilu nasional dan pemilu lokal tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon mendalilkan bahwa praktik pemilu lima kotak justru mencederai asas-asas dasar pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bukan hanya itu, sistem ini dinilai berdampak pada memburuknya kualitas representasi politik, lemahnya kaderisasi partai, hingga kerumitan administratif yang membebani penyelenggara pemilu maupun pemilih itu sendiri.
Dalam sidang putusannya, Mahkamah Konstitusi kembali memposisikan diri sebagai lembaga yang menyerahkan diskresi penataan format keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang. Sikap ini didasarkan pada prinsip negative legislator, bahwa Mahkamah tidak menciptakan hukum baru, melainkan hanya menilai apakah norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah tidak menyatakan inkonstitusionalnya pasal-pasal yang mengatur pemilu serentak lima kotak, tetapi juga tidak menyatakan bahwa sistem tersebut adalah satu-satunya bentuk yang konstitusional. Namun, narasi dan pertimbangan dalam putusan ini sesungguhnya menyimpan persoalan lebih dalam.
Pertama, Mahkamah gagal merespons kenyataan empiris yang disampaikan oleh Pemohon. Dua kali pengalaman pemilu serentak pada 2019 dan 2024 telah menunjukkan fakta: angka suara tidak sah yang tinggi, beban kerja yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu, serta kompleksitas surat suara yang menyulitkan pemilih. Mahkamah, meski mengakui bahwa keserentakan menimbulkan dampak demikian, tidak menggunakannya sebagai dasar untuk memberi pembacaan konstitusional secara lebih tajam dan solutif terhadap norma yang diuji.
Kedua, Mahkamah sesungguhnya memiliki preseden untuk membentuk norma baru melalui tafsir konstitusi yang bersifat self-executing, seperti dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang memerintahkan KPU menerima penggunaan KTP sebagai syarat memilih meski tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap. Dalam kerangka itu, Mahkamah memiliki ruang untuk menyatakan bahwa pemilu serentak yang konstitusional adalah model pemilu serentak nasional (Presiden, DPR, DPD) dan dua tahun kemudian pemilu serentak daerah (kepala daerah dan DPRD), sebagaimana ditawarkan Pemohon. Namun ruang ini justru diabaikan.
Ketiga, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menjadi rujukan Mahkamah sendiri menyebutkan bahwa pemilu serentak tidak tunggal bentuknya. Mahkamah telah menguraikan beberapa opsi model keserentakan, dan salah satunya adalah yang dipilih oleh Pemohon saat ini. Anehnya, dalam putusan yang terbaru, Mahkamah justru menutup kemungkinan untuk memilih secara tegas satu format sebagai rujukan konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang.
Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika model pemilu yang diterapkan justru menghambat ekspresi rakyat dalam menggunakan hak pilih secara jujur dan bebas, maka sesungguhnya Mahkamah berkewajiban untuk hadir melindungi hak konstitusional warga negara tersebut. Demikian pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Ketiadaan kepastian dalam model keserentakan, serta diserahkannya semua desain kepada aktor politik yang notabene memiliki konflik kepentingan elektoral, merupakan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut.
Dalam narasi besar hukum tata negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak dapat semata-mata berlindung di balik dogma negative legislator. Apalagi ketika pembentuk undang-undang belum menunjukkan sikapnya untuk mengevaluasi sistem yang ada. Dalam konteks ini, Mahkamah memiliki legitimasi konstitusional dan moral untuk bertindak sebagai positive interpreter penafsir aktif terhadap konstitusi untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga kualitas demokrasi.
Putusan ini menjadi penting apakah Mahkamah akan terus berada di jalur formalistik prosedural, ataukah berani mengambil langkah proaktif untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap bertumpu pada prinsip keadilan elektoral dan kedaulatan rakyat yang sejati. (**)