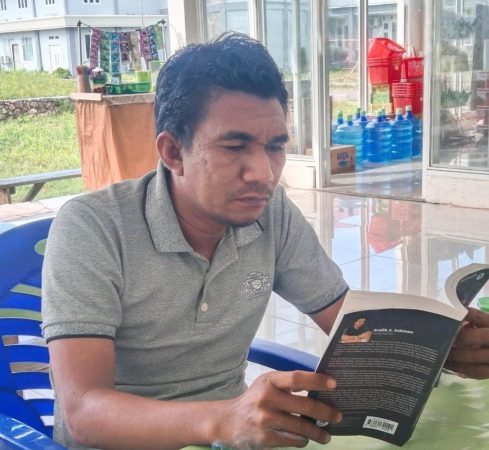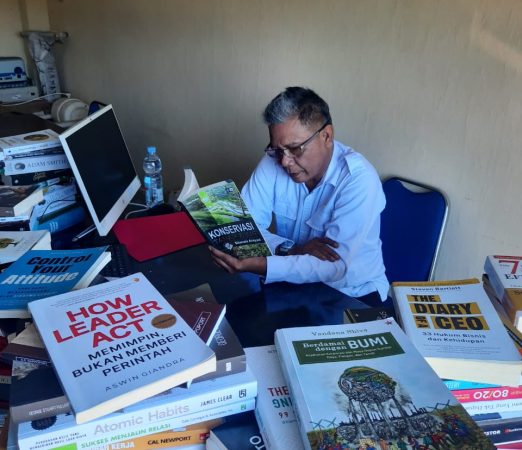“Paradoks Kemerdekaan dan Demokrasi Kita”
Oleh ; Arafik A. Rahman
“Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas dari belenggu penjajahan, tetapi juga tentang keberanian menjaga nurani dari godaan oligarki dan tirani”
KEMERDEKAAN, dalam arti filosofis bukan hanya bebas dari penjajahan asing, melainkan juga bebas dari ketakutan, dari kelaparan, dari kebodohan dan dari tirani yang dilakukan anak bangsa sendiri. Di sinilah paradoks sejarah kita : bangsa ini pernah menaklukkan penjajah bersenjata, tetapi kini sering tersandera oleh kepemimpinan yang abai terhadap jiwa demokrasi. Demokrasi yang semestinya menjadi ruang kebersamaan malah dipersempit menjadi gelanggang perebutan kursi.
Para pahlawan bangsa dahulu tidak sekadar mengangkat senjata. Mereka mengangkat martabat dan mimpi. Mereka berkorban, bukan untuk sebuah tanda tangan dalam kontrak politik, melainkan untuk darah dan jiwa yang tak kembali. Dalam setiap tetesan keringat dan darah mereka, terkandung cita-cita tentang keadilan sosial, tentang rakyat kecil yang berhak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.
Sejarah dunia memberi kita cermin. Revolusi Amerika pada 1776 melahirkan Deklarasi Kemerdekaan yang menyatakan, “All men are created equal.” Thomas Jefferson mengingatkan, bahwa martabat manusia adalah fondasi republik. Sementara Revolusi Perancis pada 1789 menggema dengan semboyan “Liberté, Égalité, Fraternité.” Dua revolusi besar itu lahir dari penderitaan rakyat yang muak terhadap penindasan; persis seperti bangsa Indonesia yang merebut merdeka 1945 dengan semangat gotong-royong melawan kolonialisme.
Kata Tan Malaka, “perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal mengusir penjajah, tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia berdiri dengan kedaulatan penuh, kesadaran politik, dan keberanian untuk berpikir merdeka.” Ia menekankan pentingnya kesadaran berpikir rasional, materialisme dan logika agar bangsa ini tidak hanya merdeka secara formal, tetapi juga mampu berdiri mandiri. Sebab, kemerdekaan tidak akan diberikan oleh siapa pun. Ia hanya bisa diwujudkan oleh bangsa itu sendiri.
Sementara pesan Bung Karno “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” Kata-kata itu tidak sekadar slogan, melainkan peringatan keras. Sebab tanpa meneladani pengorbanan pahlawan, kemerdekaan hanya tinggal upacara. Di Perancis, Maximilien Robespierre mengatakan, “The secret of freedom lies in educating people, whereas the secret of tyranny is in keeping them ignorant.” Kutipan ini mengingatkan kita: kemerdekaan tanpa pendidikan adalah kebohongan, demokrasi tanpa pengetahuan adalah jebakan.
Dari Amerika, Benjamin Franklin menegaskan: “Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.” Kata-kata ini terasa relevan di era kini, ketika elite politik kadang menggadaikan nilai kebebasan demi keamanan semu atau kepentingan sesaat. Apalagi saat publik menyaksikan praktik amnesti dan abolisi yang diberikan kepada elite politik yang terjerat masalah hukum. Apa artinya hukum ditegakkan, jika pada akhirnya kekuasaan mampu melunakkan palu keadilan?. Rakyat kecil dituntut taat, tetapi mereka yang berada di puncak kekuasaan justru mendapat karpet merah pengampunan.
Tak hanya di Senayan di pelosok negeri pun terjadi, kita menyaksikan paradoks yang sama. Di Kabupaten Pati di Jawa Tengah, misalnya. Di atas kertas, demokrasi lokal di Pati seharusnya menjadi ruang rakyat menyuarakan aspirasi. Tetapi dalam praktiknya, kontestasi politik kerap hanya menjadi perebutan kuasa antar-elite bukan kompetisi gagasan. Pilkada di Pati pernah menampilkan wajah getir demokrasi: calon tunggal yang “diterima” tanpa lawan, membuat rakyat kehilangan ruang untuk benar-benar memilih. Inilah demokrasi yang secara prosedural sah, tetapi secara substansial parah.
Pati dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil pertanian dan perikanan. Namun ironisnya, banyak petani tembakau, tebu dan nelayan masih hidup dengan kesulitan. Pajak naik, rakyat menjerit dan bermuara pada aksi massa sekabupaten yang menuntut bupatinya turun dari jabatan. Demokrasi yang mestinya memberi ruang khusus untuk keadilan dan kesejahteraan berubah menjadi petaka 13 Agustus tahun 2025 kemarin.
Kita pun melihat potret serupa di Maluku Utara. Tambang-tambang besar yang masuk ke tanah Halmahera justru sering meninggalkan luka ekologis. Sungai tercemar, hutan gundul, laut keruh. Ketika rakyat kecil bangkit membela haknya, mereka tak jarang berhadapan dengan jeruji. Kasus penangkapan 11 warga Halmahera Timur baru-baru ini adalah bukti getir: mereka ditangkap karena mempertahankan tanah dan air yang menjadi sumber hidupnya.
Apa artinya merdeka jika rakyat tidak berhak membela tanah leluhur?. Bukankah pahlawan dahulu pun angkat senjata karena ingin merebut kembali hak yang dirampas? Pati dan Halmahera adalah dua wajah berbeda dari republik yang sama: demokrasi yang seharusnya menyatukan dan mensejahterakan, justru sering berubah menjadi arena jual beli kekuasaan dan kompromi bisnis.
Dari pusat hingga daerah, wajah oligarki sering sama: rakyat hanya jadi angka dalam daftar pemilih, bukan suara yang harus diutamakan. Di sinilah ironi itu kian jelas. Jika dahulu pahlawan menolak tunduk pada kekuasaan asing, kini sebagian wakil rakyat justru tunduk pada kuasa uang. Jika dahulu darah tumpah untuk menegakkan kedaulatan, kini tinta perjanjian politik lebih sering dipakai untuk menegakkan kepentingan pribadi.
Kita pernah punya sosok-sosok yang menjelma teladan yang rela lapar demi rakyat kenyang, yang rela mati demi rakyat hidup. Bandingkan dengan hari ini: kita melihat pemimpin yang rela rakyat lapar asalkan kursi empuk tak tergoyahkan. Di sinilah fakta sejarah menertawakan kita: betapa sulitnya melahirkan kembali jiwa pahlawan di tubuh politik modern. Ada kisah yang beredar di kalangan mahasiswa: seandainya pahlawan yang gugur dahulu bangkit kembali, mereka mungkin akan salah masuk gedung.
Mereka menyangka gedung DPR adalah benteng perjuangan rakyat, padahal di dalamnya mereka hanya menemukan pasar besar tempat suara rakyat dilelang. Sementara rakyat di luar hanya bisa berteriak, seperti pedagang kecil yang tak kebagian lapak. Kisah ini bukan sekadar lelucon, melainkan potret getir. Pahlawan yang dahulu mengenal makna merdeka kini akan kebingungan melihat bagaimana kemerdekaan ditafsirkan.
Bagi mereka, merdeka berarti rakyat terbebas dari penderitaan. Namun bagi sebagian elite hari ini, merdeka berarti bebas memperkaya diri tanpa malu. Sementara itu, sastra memberi kita bahasa untuk menyindir. Dalam cerita rakyat, raja yang zalim selalu jatuh oleh doanya orang-orang miskin. Dalam kisah modern, wakil rakyat yang korup ibarat badut dalam panggung republik: tertawa sendiri, padahal rakyat menangis.
Bayangkanlah perbedaan ini: seorang pahlawan di medan perang merelakan tubuhnya ditembus peluru. Seorang pemimpin di ruang rapat justru merelakan pasal-pasal hukum ditembus kepentingan. Keduanya sama-sama berdarah: yang satu darah kemerdekaan, yang satu darah demokrasi yang ditikam. Kisah sejarah lain menyebutkan bahwa ketika pahlawan gugur, bendera setengah tiang dinaikkan.
Tetapi ketika wakil rakyat tidur saat sidang, rakyat hanya bisa menundukkan kepala sambil berbisik: “Bendera kita ternyata tidak setengah tiang, melainkan setengah hati.” Di ruang akademis, sering disebut bahwa bangsa yang lupa sejarah akan dihukum mengulanginya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah bangsa yang mengkhianati cita-cita sejarah. Sebab di situ, pengkhianatan bukan lagi kepada masa lalu, tetapi kepada masa depan.
Kita masih menyimpan banyak monumen pahlawan di tengah kota. Namun ironisnya, monumen itu lebih sering dijadikan latar swafoto ketimbang perenungan. Rakyat muda lebih akrab dengan nama selebriti ketimbang nama pejuang. Sementara wakil rakyat lebih rajin berfoto di depan patung pahlawan ketimbang meneladani hidupnya. Sejarah kembali mengetuk: apakah patung-patung pahlawan itu sengaja dibuat dari batu agar mereka tidak bisa menangis melihat generasinya?. Iya mungkin begitu.
Demokrasi seharusnya adalah ruang pendidikan politik. Namun di negeri ini, ia sering tereduksi menjadi sekadar hitung-hitungan suara. Demokrasi kita masih sebatas festival lima tahunan, bukan partisipasi harian. Yang tersisa hanyalah pesta yang meninggalkan sampah janji-janji. Kemerdekaan adalah proyek yang belum selesai. Ia harus terus diperjuangkan, bahkan melawan sesama anak bangsa yang berusaha mereduksi maknanya.
Demokrasi pun demikian: ia bukan hadiah sekali jadi, melainkan perjalanan panjang yang penuh luka dan pengorbanan. Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan bukan hanya pemimpin, tetapi negarawan. Bukan hanya perumus undang-undang, tetapi penjiwa cita-cita. Paradoks kemerdekaan dan demokrasi kita bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan cermin untuk bercermin diri.
Sejarah mungkin menertawakan hari ini, tetapi harapan untuk menjadi lebih baik selalu menanti di esok hari. Sebab di balik semua kekecewaan, masih ada keyakinan bahwa semangat pahlawan tak pernah benar-benar mati: ia hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali oleh generasi yang setia pada makna sejati kemerdekaan dan demokrasi.
Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 (1945–2025). Jayalah selalu bangsaku. Sekali merdeka tetap merdeka! (**)