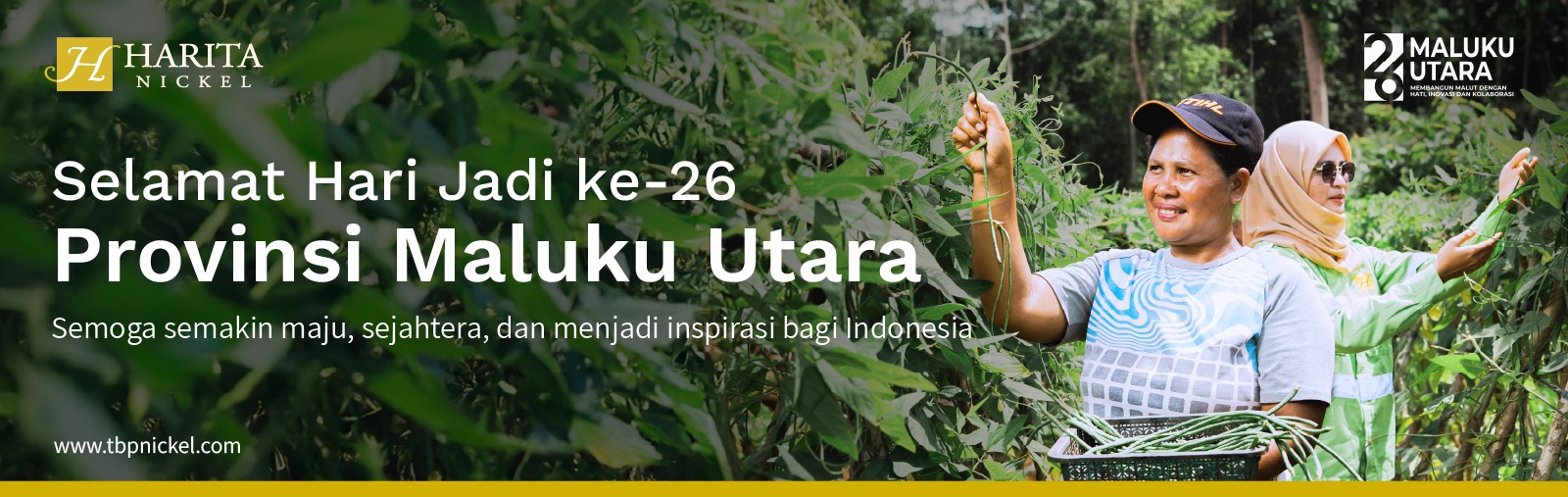“Tambang, Tunjangan dan Pajak: Tragedi Demokrasi Kita”
Oleh ; Arafik A Rahman
INDONESIA, sedang menghadapi rentetan paradoks: di saat rakyat menjerit menanggung beban pajak yang kian berat, para wakil di Parlemen justru menikmati tunjangan fantastis, sementara kerusakan lingkungan akibat pertambangan tak kunjung diperbaiki. Inilah tragedi demokrasi kita dengan tiga babak utama: tambang, tunjangan dan pajak.
Tambang yang merajalela di berbagai daerah atas nama lapangan kerja dan kepentingan negara, padahal justru negara yang paling dirugikan berkisar triliunan rupiah dibandingkan dengan kelompok korporasi. Dan yang paling tragis, tangan kita sendiri yang memberi izin agar alam dibabat habis, memperparah krisis lingkungan serta merugikan rakyat yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem.
Tan Malaka sejak lama telah mengingatkan: “Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang sejati, bukan hak istimewa segelintir orang.” Kalimat ini menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir elite yang menggunakan dalih pembangunan untuk merampas sumber daya alam.
Data resmi menunjukkan bahwa anggota DPR RI menerima tunjangan rumah senilai Rp.50 juta per bulan, menggantikan fasilitas rumah dinas yang dihapus, meski gaji pokok relatif kecil. Tak berhenti di situ, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir membenarkan adanya penyesuaian tunjangan, termasuk tunjangan beras yang naik dari sekitar Rp.10 juta menjadi Rp.12 juta per bulan. Tunjangan bensin pun melonjak, dari sebelumnya Rp.4–5 juta menjadi Rp.7 juta per bulan. Dengan berbagai pos tersebut, total gaji dan tunjangan anggota DPR bisa menembus Rp 230 juta per bulan (Kompas.com, 20 Agustus 2025).
Bayangkan, di saat rakyat harus memutar otak agar dapur tetap berasap, wakilnya justru diguyur tunjangan beras miliaran rupiah dalam setahun. Bahkan kebutuhan bensin pun disubsidi negara, ketika masyarakat umum harus membayar harga BBM yang terus berfluktuasi. Bagaimana mungkin rakyat digempur pajak, sementara wakilnya hidup dalam kemewahan?. Tunjangan sebesar itu ibarat bom sosial, terlebih ketika rakyat masih bergulat dengan kebutuhan dasar. Demokrasi seakan ditukar dengan angka, bukan dengan nurani.
Beban pajak tidak hanya meningkat; ia benar-benar menambah derita rakyat kecil. Seorang buruh di Cirebon, misalnya, harus menanggung pajak bumi dan bangunan yang melonjak dari sekitar Rp.389 ribu di tahun 2022 menjadi Rp 2,37 juta pada 2024. Padahal pendapatannya hanya Rp 10 ribu per hari. Ironi ini jelas menunjukkan ketidakadilan fiskal yang telanjang.
Sementara rakyat membayar pajak demi memenuhi kebutuhan dasar, wakil yang diharapkan memperjuangkan keadilan justru seakan mengambilnya dengan tunjangan eksesif. Demokrasi terasa dijual demi angka, bukan demi kepentingan rakyat. Ketegangan ini bahkan sudah meledak di jalanan. Pada 25 Agustus 2025, bentrokan pecah antara polisi anti-huru hara dan mahasiswa yang memprotes tunjangan besar DPR. Tunjangan rumah Rp.50 juta per bulan memicu kemarahan rakyat hingga mereka mendekati gedung parlemen.
Dilain sisi, Ketua DPR, Puan Maharani membela kenaikan tunjangan dengan alasan penyesuaian terhadap biaya hidup Jakarta. Namun argumentasi ini mengabaikan realitas: rakyat menghadapi kenaikan pajak tanpa kompensasi setimpal, sementara kerusakan lingkungan akibat tambang terus meluas. Ekonom menilai kebijakan ini akan memperburuk ketidakpercayaan publik.
Sementara itu, dari sisi teori demokrasi, Robert A. Dahl dalam bukunya Democracy and Its Critics (1989) mengingatkan: “Demokrasi hanya bisa bertahan bila pemerintah memperlakukan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, bukan sekadar penyumbang pajak.” Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya legitimasi moral dalam praktik demokrasi, bukan sekadar legitimasi angka di APBN.
Di sisi lingkungan, tambang ilegal memporak-porandakan tanah, air dan udara. Kerusakan jangka panjang ruang hidup, mata pencaharian, dan bahkan iklim lokal terus menyiksa masyarakat tanpa kompensasi memadai. Alam seolah dijadikan tumbal untuk menambal kekosongan kas atau menumpuk kekayaan kelompok tertentu.
Contoh paling nyata dapat dilihat di Maluku Utara, khususnya di Pulau Obi dan Halmahera. Aktivitas pertambangan nikel di kawasan itu telah mengubah wajah desa-desa pesisir: laut yang dahulu jernih kini tercemar limbah, hutan mangrove yang menjadi benteng alami dirusak dan nelayan kehilangan sumber mata pencaharian karena ikan semakin sulit didapat. Warga di sekitar tambang berulang kali mengeluhkan air yang keruh dan tanah yang tidak lagi subur, tetapi suara mereka sering kali diabaikan. Ironi ini menggambarkan dengan telanjang bagaimana alam dikorbankan demi kepentingan segelintir pemodal, sementara rakyat lokal harus menanggung beban ekologis tanpa perlindungan memadai.
Ruang-ruang “tambang-tunjangan-pajak” ini saling menguatkan: iuran pajak yang susah dikendalikan, tunjangan yang eksesif dan tambang tanpa pengawasan, menciptakan simbiosis antara kepentingan elite dan kerusakan bersama. Nasib buruh, petani dan warga terdampak lingkungan yang terabaikan. Mereka yang seharusnya menjadi pusat perhatian demokrasi justru ditempatkan di pinggiran. Demokrasi yang lahir dari darah perjuangan rakyat kini tampak hanya menjadi kursi empuk bagi segelintir elit.
Anggota DPR kerap membandingkan kenaikan tunjangan dengan naiknya harga beras atau kebutuhan pokok. Padahal yang benar-benar naik hanyalah tunjangan rumah, bensin dan beras mereka sendiri sementara rakyat harus berhemat. Retorika seperti ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga melukai akal sehat rakyat. Tragedi demokrasi ini semakin jelas terlihat ketika sistem yang seharusnya melindungi rakyat malah mengeruk keuangan publik demi segelintir elite. Apa yang diharapkan sebagai “wakil rakyat” justru menjadi “wakil diri sendiri”.
Di titik inilah relevan mengingatkan pesan Mohammad Hatta: “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.” Demokrasi hanya bisa bertahan jika keberpihakan ditujukan kepada rakyat kecil di desa, petani, nelayan, dan buruh bukan kepada elite yang hidup dalam privilese.
Tentu dibutuhkan reformasi tunjangan, penurunan drastis atau setidaknya transparansi penuh. Pajak perlu dikenakan secara adil, sesuai kemampuan ekonomi rakyat. Tambang ilegal harus segera diberantas, dengan program pemulihan lingkungan yang berjalan paralel. Rakyat menuntut ruang demokrasi yang benar di mana wakil rakyat hidup sederhana, peduli dan responsif terhadap penderitaan masyarakat. Bukan hidup dalam barikade privilese. Tiga unsur tragedi ini tambang yang mencabik alam, tunjangan yang melipat gaji, dan pajak yang menindas rakyat, melambangkan moral demokrasi yang rapuh, jika tidak dikoreksi segera.
Tan Malaka juga pernah menegaskan: “Setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, sehalus-halusnya laku, kalau tidak kembali kepada rakyat, tidak akan ada artinya.” Kutipan ini adalah alarm keras: demokrasi yang kehilangan orientasi pada rakyat hanyalah topeng kosong yang melayani kepentingan elite.
Hanya dengan tekanan publik yang konsisten, transparansi kebijakan, dan reformasi struktural, demokrasi bisa kembali kepada fungsinya: penyeimbang yang menegakkan keadilan, bukan alat eksploitasi. Kita menghadapi paradoks yang meresahkan: wakil rakyat yang seharusnya melindungi justru hidup mewah; rakyat yang seharusnya dilindungi justru menanggung tekanan ekonomi; dan bumi yang seharusnya diolah bijaksana justru dirusak habis-habisan.
“Demokrasi bukan soal fasilitas mewah, tunjangan melangit, dan gaya-gayaan di gedung megah, tetapi bagaimana mengayomi dan memastikan keadilan serta kesejahteraan untuk rakyatnya.” (**)